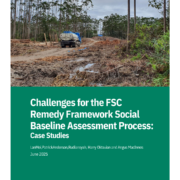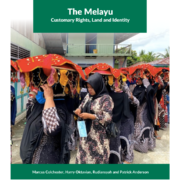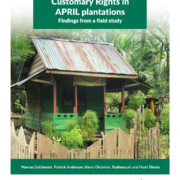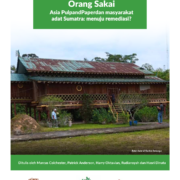Istilah Melayu tampaknya berasal dari abad ke-4 atau ke-5 Masehi yang merujuk pada kerajaan-kerajaan Buddha awal yang muncul di Sumatra Selatan yang berusaha menguasai dan berkontribusi pada perdagangan antarbenua antara Tiongkok dan India serta Timur Tengah. Awalnya, istilah ini merujuk pada keluarga kerajaan dari kesultanan-kesultanan ini, yang dengan cepat menyebarkan jaringan mereka ke seluruh perairan Asia Tenggara, baru kemudian istilah ini diterapkan pada berbagai masyarakat yang mereka kuasai dan kemudian lebih luas lagi pada semua penutur rumpun bahasa yang tersebar di seluruh wilayah tersebut. Saat ini, istilah Melayu digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat untuk mengidentifikasi diri mereka yang memiliki riwayat hubungan dengan kesultanan-kesultanan ini yang telah memeluk agama Islam.
Penelitian ini menunjukkan bagaimana – berdasarkan pengambilan sampel dan bukan survei menyeluruh – banyak dari berbagai kelompok masyarakat yang kini menganggap diri mereka sebagai orang Melayu masih menjunjung tinggi hubungan mereka dengan tanah dan lingkungan mereka berkenaan dengan konsep tradisional yang mungkin mendahului pemelukan agama Islam. Dengan demikian, kita menemukan masyarakat ‘Melayu’ yang memiliki sistem penguasaan tanah yang mirip dengan orang Minangkabau di Sumatra Barat, yang berdasarkan garis keturunan ibu/matrilineal, atau masyarakat hutan Bathin di Sumatra Timur, orang Dayak di Kalimantan, dan seterusnya. Mereka mungkin telah mengadopsi Islam dan hukum syariah, mereka mungkin menganggap diri mereka ‘modern’, tetapi dalam hal bagaimana mereka memerintah dan berkaitan dengan wilayah, tanah, dan sumber daya mereka, mereka mempertahankan versi hukum adat yang dimodifikasi, yang memiliki akar yang jauh lebih dalam.
Temuan-temuan ini memiliki implikasi besar terhadap bagaimana hak-hak masyarakat ini kini diperhitungkan oleh pemerintah, lembaga-lembaga pembangunan dan perusahaan – dan sistem sertifikasi sukarela seperti FSC. Laporan ini diakhiri dengan serangkaian rekomendasi tentang bagaimana masyarakat-masyarakat ini harus diperlakukan secara lebih adil di masa mendatang.
Studi ini dibangun berdasarkan kerja sama selama bertahun-tahun antara Forest Peoples Programme, yang berpusat di Inggris, Bahtera Alam, yang berpusat di Riau, dan Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari, yang berpusat di Jakarta, dalam mendukung ‘masyarakat hutan’ – yang kami artikan sebagai masyarakat yang telah lama tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan, yang mengklaim hak adat atas tanah mereka.1 Dua dari tiga penulis naskah ini mengidentifikasi diri sebagai orang Melayu.
Program-program lapangan dari berbagai organisasi kami dalam mendukung masyarakat Melayu di Kalimantan dan Sumatra dalam dua decade terakhir ini telah membuat kami menyadari bahwa meskipun masyarakat Melayu mengklaim identitas yang sama dan menganut agama yang sama – Islam – cara mereka berhubungan dengan tanah mereka dan mengklaim hak atas tanah tersebut sering kali sangat berbeda.
Berbeda halnya dengan literatur tentang masyarakat Dayak di Kalimantan dan masyarakat lainnya seperti Minangkabau di Sumatra Barat, relative sangat sedikit LSM dan studi akademis tentang masyarakat Melayu yang berupaya mendokumentasikan sistem penguasaan tanah mereka atau, bahkan lebih sedikit lagi, untuk mengartikulasikan klaim dan harapan mereka tentang tanah dan sumber daya mereka saat berurusan dengan pemerintah dan sektor swasta.
Penelitian ini merupakan upaya sederhana untuk mengoreksi kesenjangan yang ada ini, yang didorong oleh fakta bahwa transformasi besar sedang berlangsung di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan remediasi atas ‘kerugian sosial’ yang diderita oleh masyarakat akibat dampak dari sektor kayu pulp antara tahun 1994 dan 2020, sejalan dengan Kebijakan baru Forest Stewardship Council (FSC) untuk Mengatasi Konversi, Kebijakan Asosiasi yang direvisi, dan Kerangka Kerja Remediasi yang baru-baru ini diadopsi.
FSC menawarkan sebuah prosedur di mana masyarakat yang mengidentifikasi diri sebagai masyarakat adat dan ‘masyarakat tradisional’ lainnya yang memiliki hak-hak adat, baik yang telah maupun yang belum diakui oleh hukum perundang-undangan, dapat memperoleh remediasi atas kerugian yang ditimbulkan kepada mereka oleh perusahaan yang ingin berasosiasi dengan FSC dan kemudian memperoleh sertifikasi sesuai dengan standarnya.
Penelitian ini didasarkan pada tinjauan pustaka, refleksi atas pengalaman lapangan lembaga-lembaga kami selama tiga puluh tahun terakhir, sebagai organisasi hak asasi manusia dan organisasi pendamping yang bekerja dengan masyarakat yang mengidentifikasi diri sebagai orang Melayu, dan didasarkan atas serangkaian kunjungan lapangan singkat ke wilayah masyarakat Melayu di Riau yang dilakukan oleh para penulis bersama pada bulan Mei 2024.
Kami mengunjungi masyarakat Batu Songgan, di tepi barat Riau di kaki pegunungan Barisan Nasional; masyarakat Lubuk Jering, di dataran sebelah utara Pekanbaru di pusat provinsi, dan masyarakat Teluk Meranti, di muara sungai Kampar ke arah timur (lihat Peta 1).
Survei lapangan dilakukan dengan melakukan perjalanan ke, mengunjungi, dan tinggal sebentar dengan komunitas-komunitas ini, di mana kami meminta warga untuk berpartisipasi dalam wawancara dan bergabung dengan kelompok diskusi untuk menjelaskan hubungan mereka dengan tanah mereka dan membahas tantangan yang mereka hadapi saat ini dalam mengamankan hak-hak mereka. Kami menganggap kerja ini lebih bersifat ilustratif daripada definitif dan mendorong pihak lain dari lingkup akademis dan masyarakat sipil untuk memperdalam bidang pengetahuan ini.
Bisa unduh laporannya di bawah ini:
Orang Melayu – Bahasa Indonesia
The Melayu – Bahasa Inggris