Hari Pangan Sedunia: Hentikan Kriminalisasi, Upayakan Perlindungan, dan Pelibatan Masyarakat Adat dalam Kebijakan Pembangunan
Siaran Pers
Yayasan Pusaka Bentala Rakyat
Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari
Tuntutan dan Desakan dari Masyarakat Adat Papua Barat Daya Pada Perayaan Hari Pangan Sedunia: “Hentikan Kriminalisasi, Upayakan Regulasi Perlindungan Kepada MA, dan Pelibatan MA dalam Kebijakan Pembangunan”
Sorong, Papua Barat Daya, 16-18 Oktober 2025
Sejak awal tumbuh suburnya perusahaan sawit di Sorong, belum ada tindakan pemerintah yang mengevaluasi beroperasinya perusahaan. Apakah sudah taat pada aturan kehutanan, pertanian atau perkebunan. Juga bagaimana penyelesaian konflik dengan masyarakat adat pemilik hutan yang masuk dalam wilayah konsesi. Salah satu alasan karena industri ekstraktif SDA erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang umumnya terjadi dalam situasi politik praktis berbiaya mahal di mana kandidat pemimpin daerah mendapatkan biaya politik dari pengusaha dan membalasnya dengan cara memberi konsesi SDA pasca terpilih. Cara ijon politik perizinan ini banyak terbukti inkracht secara hukum terutama periode dimana KPK banyak menyoroti permasalahan korupsi sektor SDA – KPK GNPSDA.
Pada tahun 2021 Pemda Provinsi Papua Barat berdasarkan review perizinan KPK melakukan penindakan perizinan sektor SDA – khususnya perusahaan perkebunan sawit. Tindakan ini perlu diapresiasi dan dilihat lagi sebagai milestone perbaikan tata kelola SDA karena masa kebelakang hampir tidak ada upaya serupa itu. Momentum ini bahkan memicu Pemda Sorong dan Sorong Selatan untuk mengambil tindakan administratif lebih serius dengan mencabut beberapa tahapan perizinan perusahaan sawit yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.
Riset Yayasan Pusaka (2024) tentang Investasi Sawit di Sorong berjudul “Investasi Bodong: Mengungkap Beban dan Manfaat dari Investasi Sawit di Tanah Papua” menemukan permasalahan dari pendudukan perkebunan sawit di level masyarakat di kampung orang asli Papua di mana banyak masalah seperti pelepasan tanah adat yang melanggar hukum adat serta UU Otsus Papua dan sawit plasma masyarakat yang tidak sesuai aturan.
Menurut Wiko Saputra, kehadiran investasi sawit di tanah Papua tidak banyak menguntungkan masyarakat adat. Ada banyak izin perusahaan yang tidak sesuai dan tidak tunduk pada peraturan serta kebijakan negara.
“Per tahun rakyat Papua harus rugi 96 triliun akibat okupasi sawit di tanah Papua. Tidak ada dampak dan manfaat baik yang diterima oleh masyarakat adat Papua. Yang diterima masyarakat hanyalah beban sosial, beban kerusakan lingkungan, dan beban ekonomi,” tegas Wiko.
Menurut Wiko, ada banyak modus perusahaan mengakali kewajiban 20 persen plasma oleh perusahaan sawit. Banyak plasma diubah menjadi bantuan, bangun infrastruktur, buat program pemajuan ekonomi yang dihitung sebagai kewajiban plasma perusahaan. Padahal ini melanggar secara aturan bagaimana skema pemberian kewajiban plasma oleh perusahaan sawit.
“Temuan KPK juga menunjukan baru ada 28 persen perusahaan sawit di Indonesia yang telah merealisasikan kewajiban plasma. Dan untuk Papua angkanya masih sangat kecil,” tambah Wiko lagi.
Dalam hasil risetnya “Sawit Investasi Bodong”, Wiko juga menegaskan bahwa temuan riset mereka bisa berimplikasi pada banyak hal salah satunya masalah besar yang akan dihadapi oleh masyarakat Papua, yakni mengenai krisis pangan. Papua menjadi nomor 1 kerawanan pangan di Indonesia. Jika ini terjadi akan berbanding terbalik dengan apa yang ada di Papua. Wilayah yang kaya akan sumber daya alamnya kini dalam ancaman kerawanan pangan akibat investasi sawit yang tidak memberikan keuntungan kepada masyarakat dan lebih banyak merugikan.
“Salah satu solusinya adalah dengan mendorong pemerintah membentuk tim audit plasma independen yang didalamnya diisi oleh masyarakat adat, OMS, dan pemerintah. Dan mempertegas hasil penertiban kawasan hutan oleh satgas dikembalikan ke masyarakat bukan ke perusahaan negara seperti Agrinas,” tegas Wiko.
Nelson Kutumun dari Suku Moi Sigin Distrik Moisigin berbagi cerita dari kampungnya sejak perusahaan sawit masuk tahun 2007 yang telah melakukan pembongkaran tanah masyarakat adat. Perusahaan membuat komitmen dan janji kepada masyarakat dengan alasan tanah akan kembali dan perusahaan hanya mendapat izin kelola atau izin pakai saja. Setelah masa kontrak itu berakhir tanah akan kembali kepada masyarakat lagi. Akan tetapi, semua itu tidak seperti yang terbayangkan.
“Saat saya mengecek isi perjanjian dan kontrak, saya menyesal. Semua kesepakatan itu tidak ada. Tidak ada dalam kontrak tanah akan kembali. Semua akan diserahkan ke negara jika masa kontrak perusahaan selesai,” kata Nelson pada diskusi memperingati hari pangan di Sorong, Sabtu 18 Oktober 2025.
Nelson, masyarakat adat dari Moi Sigin ini menyayangkan juga sejak kehadiran perusahaan sawit di kampungnya hutan dan dusun sagu hilang. Hutan terlarang yang sakral diterobos oleh perusahaan sawit. Bahkan, ada satu kalimat dalam kontrak yang Nelson baca, yang berbunyi, ”semua hasil yang ada di perut bumi yang masuk dalam wilayah pengelolaan perusahaan hak perusahaan”. Padahal perjanjian awalnya semua hasil bumi yang masuk izin masih bisa dikelola oleh pribumi atau masyarakat adat.
“Parahnya lagi. Ada kalimat seperti ini ‘semua hal buruk yang terjadi bukan tanggung jawab pihak kedua. Pihak kedua dalam hal ini perusahaan’. Saya mau ingatkan kepada kalian semua, jangan main-main dengan sawit. Karena kerugiannya tidak sedikit,” ucap Nelson dengan tegas pada sesi diskusi.

Yulius Marinow Masyarakat Adat terdampak perkebunan sawit berbagi ceritanya mengenai dampak buruk yang dirasakan anggota marganya saat perusahaan sawit hadir di kampung. Yulius hadir dan berbagi cerita pada sesi diskusi hasil riset investasi sawit bodong di tanah Papua dalam rangkaian kegiatan memperingati hari pangan internasional, Sorong, Rabu (16/10/2025).
Pemerintah Kabupaten Sorong pada tahun 2021 berhasil mencabut 4 izin usaha perkebunan sawit dari 7 konsesi sawit yang ada di Kabupaten Sorong. Alasan dasar pencabutan izin berawal dari evaluasi perizinan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat yang dimulai sejak Juli 2018, sebelum Papua Barat Barat menjadi satu Provinsi sendiri (pemekaran Papua Barat) pada tahun 2022 karena revisi UU Otsus Papua Jilid II.
Alasan lainnya dalam Deklarasi Manokwari bahwa Papua Barat sebagai Provinsi konservasi. Juga tertuang dalam Inpres Nomor 8 tahun 2018 tentang Penundaan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Sawit (Inpres Moratorium Sawit) dan Koordinasi dan Supervisi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA) KPK.
Empat perusahaan sawit yang dicabut itu adalah PT Inti Kebun Lestari, PT Cipta Papua Plantation, PT Papua Lestari Abadi, dan PT Sorong Agro Sawitindo. Keempat perusahaan ini dari hasil evaluasi telah melakukan pelanggaran administrasi seperti tidak memiliki IPK, IUP, HGU, dan tidak memiliki kepemilikan pelaporan saham dan kepengurusan.
“Hal yang lain lagi adalah perusahan sawit ini tidak ada laporan perubahan pemilik saham dan tidak memiliki Hak Guna Usaha,” kata Demianus Aru, selaku Kabag Hukum Kabupaten Sorong, pada sesi diskusi perayaan pangan internasional di Sorong, Jumat (17/10/2025).
Beberapa Perusahaan sawit yang dicabut pun melawan balik melalui PTUN Jayapura kendatipun kalah. Tetapi upaya lanjutan mereka menang pada tingkat banding di PTTUN. Ada juga yang tidak melakukan pembelaan hukum. Di Sorong bahkan hingga kini ada perusahaan yang menempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK) di MA sebagai upaya mendapatkan kembali konsesinya.
Kabag Hukum itu juga menuturkan, perusahaan sawit yang melanggar administrasi ini sangat merugikan masyarakat adat. Kerugian telah banyak ditimbulkan akibat perusahaan sawit tersebut. Dia juga mengatakan masyarakat saat ini jangan mudah terpancing dengan cepat menjual tanah adatnya.
Devianti Sesa Perempuan Adat dari Kampung Wehali Sorong Selatan, mengatakan bahwa masyarakat adat di Papua jangan menjual tanah. Karena tanah dan perempuan itu sangat erat. Harus berkaca dari perusahaan sawit yang hadir di kampung-kampung. Tanah lepas, pangan dan kehidupan juga ikut terdampak. Makanya perlu mengupayakan perlindungan dari sekarang terhadap tanah-tanah di kampung.
“Kami sadar pasti akan datang investasi. Tapi kami perlu perlindungan dengan dibuatnya regulasi untuk menjaga tanah adat dan pangan di tingkat kampung. Agar masyarakat adat bisa merasa aman wilayahnya dan tidak akan mudah diambil oleh perusahaan,” tuturnya dalam sesi diskusi.
Devianti yang hadir sebagai narasumber saat itu menjelaskan bagaimana perempuan di kampungnya selalu masuk keluar hutan untuk mencari bahan membuat noken. Kesehariannya yang sering ke hutan merupakan salah satu upaya menjaga hutan. Kalau tidak menjaga hutan kedepannya pasti akan hilang. Pangan akan hilang. Noken akan hilang. Sebab hutan sudah menjadi bagian dari kehidupan orang Papua.
Sebagai Provinsi baru, PBD mewarisi banyak masalah. Saat diskusi memperingati hari pangan 16-18 Oktober masalah itu terungkap dari kesaksian masyarakat yang hadir. Masalah itu seperti sawit plasma, kekerasan aparat dan pelepasan tanah adat yang melanggar hukum. Perwakilan masyarakat adat dari Sorong hingga Sorong Selatan bahkan Raja Ampat memaparkan setiap kondisi yang terjadi di lapangan. Ada perampasan ruang hidup, penipuan yang dilakukan perusahaan, dan paling parahnya lagi peluang masyarakat kehilangan wilayah adat dan tanahnya didukung oleh perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
Hal ini bisa dilihat dari perkembangan kebijakan tata ruang nasional melalui Kementerian ATR/BPN No.B/PB.07.01/2834/X/2024 memberikan rekomendasi peninjauan kembali bahwa RTRW Provinsi Papua Barat Daya 2025-2045 perlu direvisi.Revisi ini merujuk pada UU No.59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045 dengan fokus arah kebijakan transformasi ekonomi untuk Papua Barat Daya:
| 1. | Pengembangan komoditas unggulan bernilai tambah tinggi dan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan |
| 2. | Pengembangan pariwisata unggulan dan ekonomi kreatif |
| 3. | Pembangunan ketenagalistrikan |
| 4. | Pengembangan dan peningkatan pada pelabuhan-pelabuhan simpul utama di sebagai transhipment hub domestic di Pelabuhan Sorong |
Perubahan kebijakan tata ruang ini tentu saja dimaksudkan untuk mengakomodir kebijakan pembangunan Jakarta di Papua dengan fokus pembangunan yang telah ditentukan di awal untuk diterapkan ke seluruh Papua. Jika membaca perencanaan kebijakan dengan kondisi di lapangan nampaknya ketegangan masih akan terus terjadi. Persoalan yang mendasar tentang perlindungan Orang Asli Papua dan tanahnya masih terabaikan. Seringkali kepentingan perusahaan ekstraktif didahulukan atas nama pembangunan atau kepentingan nasional mendominasi panggung wacana politik praktik kebijakan. Satu hal yang sering terlupa, perlindungan mendasar OAP seperti hak atas tanah dan hutan dalam skema hutan adat pelaksanaannya tak pernah diseriusi dalam ranah kebijakan nasional.
Menurut data BRWA hingga agustus 2025 penetapan hutan adat di seluruh Papua hanya sekitar 39.912 hektar dari potensi luasan 12.466.866 hektar. Parahnya Provinsi Papua Barat dengan lima kabupatennya yang menjadi sasaran investasi ekstraktif SDA hingga kini belum ada satupun penetapan hutan adat.
Kebijakan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga dijelaskan oleh Rahman Selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) pada sesi diskusi perayaan hari pangan internasional yang dilaksanakan di Hotel Panorama Sorong, Kamis, 16 Oktober 2025.
“Visi jangka panjang PBD sebagai pintu gerbang arah pembangunan Papua yang maju dan berkelanjutan berbasis ekonomi biru. Ekonomi biru ini sebagai pilar karena garis pantai wilayah PBD sangat luas ditunjang dengan kekayaan sumber daya lautnya,” jelas Rahman Kepala Bapperida Papua Barat Daya.
Papua Barat Daya meskipun baru seumur jagung tapi sudah matang dipersiapkan untuk arah pembangunannya ke depan. Misalnya arah pembangunan pada sektor ekonomi ekstraktif yang difokuskan pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Selain itu, arah pembangunan Papua Barat Daya juga akan mengarah kepada pengembangan potensi transisi energi yang menjunjung tinggi komitmen energi terbarukan dan rendah karbon.

Nelson, masyarakat adat dari Moi Sigin ini menyayangkan juga sejak kehadiran perusahaan sawit di kampungnya hutan dan dusun sagu hilang. Hutan terlarang yang sacral diterobos oleh perusahaan sawit.
“Akan tetapi ada risiko dalam proyek transisi energi ini. Banyak masalah di lapangan seperti masyarakat adat yang hilang tanah. Makanya pemerintah mengupayakan prinsip transisi energi yang berkeadilan dengan cara mengoptimalkan energi lokal seperti air, surya, dan laut,” tambah Rahman.
Namun, paparan Kepala Bapperida ini tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Silas Kalami selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi menjelaskan, banyak konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan dan antara masyarakat sendiri. Konflik bukan hanya memicu perkelahian tapi turut memperburuk ikatan persaudaraan antar masyarakat dan antar marga.
Menurut Silas, investasi membawa dampak buruk bagi masyarakat adat. Kondisi lingkungannya rusak sehingga ruang hidup masyarakat juga ikut terganggu. Hutan yang dulunya selalu dimanfaatkan sebagai tempat makan. Saat ini tidak bisa lagi karena semua hutan dan tanah adat berubah menjadi lahan-lahan kebun sawit dan tambang. Hal ini seharusnya menjadi pelajaran kepada semua masyarakat adat agar tidak menerima bujuk rayu investasi yang menyasar tanah adatnya. Karena keburukannya sudah bisa dilihat di depan mata dan terjadi di mana-mana.
“Masyarakat adat harus waspada dengan investasi atau proyek dari pemerintah. Harus belajar dari banyak kasus jangan menjual tanah lagi. Yang ada sekarang tanahnya harus dipertahankan. Jangan lagi dijual,” ujar Silas dalam sesi diskusi.
Apalagi kata Silas, Perda tentang perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sorong sudah tegas mengatur bagaimana investasi masuk ke tanah marga atau tanah adat harus mendapat persetujuan masyarakat adat itu sendiri. Artinya, tanah penting untuk dijaga. Alam untuk dijaga. Dan manusianya saling menjaga.
Torianus Kalami, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Malamoi, yang juga hadir sebagai pembicara pada sesi diskusi itu memberikan pandangannya tentang kehadiran investasi di tanah Malamoi. Tori menyadari regulasi perlindungan kepada masyarakat adat adalah salah satu jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi sekarang oleh masyarakat adat Papua khususnya di Malamoi.
Meskipun Perda Nomor 10 tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten Sorong sudah disahkan, tapi perjuangan dalam melindungi masyarakat adat tidak harus berhenti di situ. Perlu lagi membuat regulasi di tingkat kampung seperti membuat peraturan adat di kampung lalu didorong ke tingkat kabupaten sebagai mitigasi perlindungan masyarakat adat di kampung.
“Perda Nomor 10 ini bisa jadi sejarah awal di Papua yang membuat perlindungan untuk masyarakat adat Papua. Tapi jangan habis sampai di situ. Masih ada pekerjaan lainnya adalah dengan membuat regulasi di tingkat kampung,” kata Torianus dihadapan peserta diskusi yang dihadiri masyarakat adat dari Sorong hingga Sorong Selatan.
Akhirnya diskusi selama tiga hari tersebut ditutup dengan mendiskusikan solusi bersama dan melahirkan tuntutan kebijakan yang harus segera didorong dan dibentuk oleh pemerintah baik pemerintah Pusat dan khususnya Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Tuntutan bersama masyarakat adat dalam perayaan hari pangan sedunia

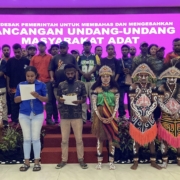

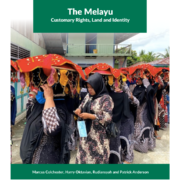



 Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari
Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari